Mengupas Gangguan Bipolar pada “Kukira Kau Rumah”
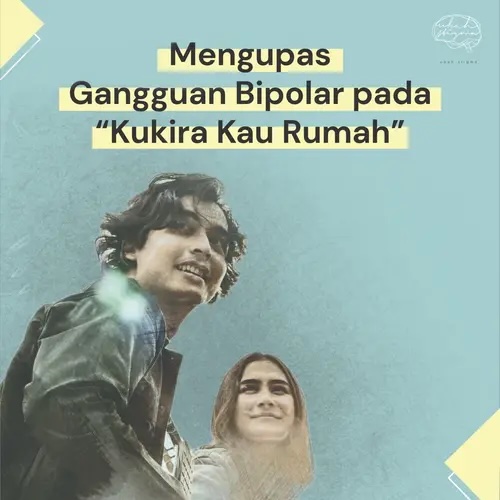
Film “Kukira Kau Rumah” yang disutradarai oleh Umay Shahab, tayang 3 Februari lalu menjadi ramai diperbincangkan lantaran mengangkat isu kesehatan mental. Dalam film ini diceritakan sosok perempuan bernama Niskala (Prilly Latuconsina) yang memiliki gangguan kesehatan gangguan bipolar. Gangguan mental tersebut membuat Niskala menjadi sosok yang begitu dijaga oleh kedua orang tuanya, khususnya sang Ayah.
Demi menjaga kestabilan mental sang anak, Ayah Niskala membatasi segala aktivitas anaknya termasuk melarangnya untuk kuliah. Namun, dengan dukungan sang Ibu, serta bantuan Dinda (Shenina Cinnamon) dan Oktavianus (Raim Laode), Niskala pun bisa berkuliah tanpa sepengetahuan sang Ayah. Dalam perkuliahan, Niskala bertemu dengan seniornya, Pram (Jourdy Pranata), dan semenjak itulah konflik cerita kehidupan Niskala dimulai.
Jadi, Apa Itu Gangguan Bipolar dalam “Kukira Kau Rumah”?
Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health-5 (DSM-5), gangguan bipolar merupakan gangguan perubahan suasana hati atau mood yang ditandai dengan dua fase, yakni fase terendah (depresi) dan fase tertinggi (manik). Episode manik identik dengan suasana hati yang terus menerus meningkat secara abnormal dan biasanya individu akan terlihat sangat energetik serta ingin melakukan banyak kegiatan di kesehariannya selama kurang lebih 1 minggu. Sedangkan, episode depresi diciri-cirikan dengan hilangnya minat, perasaan sedih, putus asa, capek, dan merasa tidak berharga.
Dalam film “Kukira Kau Rumah” tak begitu dijelaskan secara gamblang apa itu Bipolar Disorder. Perilaku Niskala yang sering ditonjolkan adalah sifat yang mudah tersulut amarah, memaki lawan bicara, dan sulit dikendalikan ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Contoh perilaku ini selaras dengan apa yang dijelaskan dalam DSM-5, salah satu gejala fase manik adalah suasana hati yang mudah tersinggung. Selain itu, Niskala juga menunjukkan perilaku berisiko, seperti pada salah satu adegan ketika dia seperti merampas gunting dari gurunya. Perilaku ini pun juga termasuk pada gejala yang muncul pada fase manik. Meskipun begitu, episode manik pada film ini hanya fokus pada suasana hati yang mudah tersinggung dan perilaku yang membahayakan diri serta orang lain, padahal fase manik pada gangguan bipolar lebih kompleks daripada itu. Malah, fase manik sangat identik dengan mood yang meninggi, rasa percaya diri yang melambung, memiliki banyak ide, berbicara tidak henti, mudah terdistraksi, dan sifat optimis yang berlebih yang tidak banyak dijelaskan dalam film ini.
Fase depresi yang dialami Niskala pada film ini tidak banyak diperlihatkan. Sekilas, ada satu adegan yang memperlihatkan ia marah, menangis, dan sulit dikendalikan lantaran ter-trigger oleh perkataan Oktavianus. Sekilas keadaan itu tampak seperti keadaan depresi. Namun, berdasarkan DSM-5, menjadi mudah tersinggung menjadi salah satu gejala manik.
Keadaan depresi Niskala sendiri terlihat usai dirinya begitu emosional kemudian berubah menjadi tenang, tak bergairah dalam melakukan aktivitas hingga menjadi sosok yang pesimistik. Hal ini digambarkan ketika Niskala mengatakan pada Pram bahwa pria tersebut harus menjauhinya dan mencari perempuan yang jauh lebih baik dan sehat secara mental. Kondisi ini berbeda dengan kepribadian Niskala saat bersama Pram sebelum fase depresi muncul. Saat itu, bersama Pram, Niskala merasa bahwa ia menemukan siapa dirinya, mendapatkan apa yang ia butuhkan dan merasa aman serta nyaman bersama Pram.
Dalam proses pendiagnosaan gangguan mental, seperti bipolar, oleh psikiater diperlukan waktu untuk mendapatkan diagnosa tegak, dan perawatan gangguan mental tidak hanya sebatas pemberian obat tapi melibatkan terapi-terapi lainnya. Proses pendiagnosaan ini tidak terjadi pada film. Ketika Niskala dan Ibunya menemui dokter, sang dokter langsung menyatakan bahwa Niskala menderita gangguan bipolar tanpa ada penjelasan atau penyampaian terkait gejala-gejala yang dialami Niskala.
Penggambaran yang kurang mendalam akan gangguan bipolar dalam film ini sangat amat disayangkan. Karena hanya dengan menunjukkan Niskala seorang penderita gangguan bipolar sebagai orang yang mudah marah, berperilaku gegabah, serta proses pendiagnosaan yang terkesan instan akan memberikan pemahaman yang tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan stigma terkait gangguan mental ini.
Citra Penderita Gangguan Bipolar yang Sulit Dikendalikan
Pada suatu adegan dimana Niskala mengamuk dan memaki orang tua serta sahabatnya, keadaan terlihat begitu kacau lantaran Niskala sulit ditenangkan dan dikendalikan. Situasi tersebut membuat Ibunya dan Dinda memaksa gadis itu mengonsumsi obat penenang khusus yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat darurat. Anjuran tersebut tertulis dalam botol obat Niskala. Sayangnya, ada hal yang dirasa kurang dan mengganggu dalam adegan tersebut, yaitu tidak dijelaskan “keadaan darurat” seperti apa yang mengharuskan seorang dengan gangguan bipolar harus mengonsumsi obat tersebut. Karena jika dilihat kembali perilaku yang muncul, Niskala terlihat menangis, marah, dan penuh emosi, yang mana keadaan ini sangat mungkin dialami oleh banyak orang pada umumnya.
Menurut ilmu psikologi, emosi negatif seperti marah adalah sesuatu yang sangat normal dialami dan ditunjukkan. Pada adegan ini pemberian obat kepada seseorang yang sedang marah untuk meredam emosi tersebut sangat, berisiko menggiring stigma negatif terkait emosi itu sendiri. Hal ini juga berisiko memberikan label bahwa ketika adanya perubahan mood yang ekstrim pada penderita gangguan bipolar, harus diberikan obat pada saat itu juga. Padahal ada cara lainnya yang bisa dilakukan untuk menangani episode manik, seperti menenangkan diri dengan mengalihkan fokus pada hal lain (mendengarkan musik, menonton, berbicara dengan orang lain), mendapat bantuan melalui psikoterapi, mendapat bantuan dari orang terdekat yang bisa membantu memahami dan mengatasi emosi, perilaku, dan pemikiran individu dengan gangguan bipolar.
Hilangnya Peran Caregiver atau Support System
Dalam menangani pasien gangguan kesehatan mental, diperlukan sebuah support system atau dukungan dari orang sekitar, seperti keluarga, sahabat, hingga terapis. Dalam “Kukira Kau Rumah” sosok support system atau caregiver seolah tidak ada. Memang, terlihat sangat jelas bahwa orang tua dan sahabat Niskala sangat menjaga kestabilan mentalnya, namun cara yang dilakukan, seperti mengekang, membatasi aktivitas, pemberian obat-obatan untuk meredam amarah, justru tidak tepat. Pada fase depresi Niskala, justru gadis tersebut dibiarkan sendirian di kamar untuk menenangkan diri. Orang tuanya juga membatasi segala aktivitas yang mana sikap ini justru lebih berarti menghindari konflik ketimbang membantu penderita gangguan bipolar belajar menghadapi konflik.
The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) and the British Association of Psychopharmacology (National Collaborating Centre for Mental Health (NCCMH) merekomendasikan intervensi psikologis dalam manajemen gangguan bipolar. Di antara beberapa jenis pendekatan intervensi psikososial yang paling sering dilakukan adalah psikoedukasi. Banyak studi menunjukkan efektivitas pendekatan keluarga, kelompok, interpersonal pada gangguan bipolar. Hal ini menunjukkan bahwa peran caregiver sebagai support system sangat dibutuhkan.
“Kukira Kau Rumah” menjadi film menarik untuk disaksikan, namun adegan yang menggambarkan gejala bipolar pastinya tidak bisa menjadi acuan untuk menilai apakah dirimu menderita gangguan bipolar atau tidak. Sebagai sebuah karya yang mengangkat isu kesehatan mental sehingga diharapkan menjadi sarana edukasi, “Kukira Kau Rumah” rasanya masih kurang memberikan informasi komprehensif terkait kompleksitas kesehatan mental itu sendiri. Wajah gangguan bipolar yang ditampilkan dalam film hanya lapisan paling luar untuk menarik masyarakat yang justru berisiko membentuk stigma baru serta membentuk sebuah self-diagnosis. Jauh lebih dalam, Bipolar Disorder bukan sekadar gangguan perubahan suasana hati dari marah, ceria dan menangis seperti yang digambarkan dalam film. Sangat diharapkan dunia perfilman Indonesia dapat membuat karya yang mengupas lebih dalam dan secara tepat mengenai kompleksitas kesehatan mental di kemudian hari.
Sumber:
- Duffy, J. (2012). Managing Anger and Aggression: Practical Guidance for Schools. South Eastern Education and Library Board: Psychology/ Behavior Support Section. Diakses melalui https://journal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/10574/7969pada 7 Maret 2022 pukul 01.00 WIB.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5(TM)) (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- How to Deal With Mania and Manic Episodes. (2020, September 3). WebMD. https://www.webmd.com/bipolar-disorder/deal-with-mania
- Warih Andan Puspitosari. The Needs of Bipolar Disorder Psychoeducation in Family Members. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses melalui http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3705/Warih_Konas%20Bipolar_2015_The%20Needs%20of%20%20Bipolar%20Disorder%20Psychoeducation%20in%20Family%20Members.pdf?sequence=1&isAllowed=y pada 7 Maret 2022 pukul 01.17 WIB
- Colom, F. (2011). Keeping therapies simple: Psychoeducation in the prevention of relapse in affective disorders. British Journal of Psychiatry, 198, 338-340 diakses melalui http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3705/Warih_Konas%20Bipolar_2015_The%20Needs%20of%20%20Bipolar%20Disorder%20Psychoeducation%20in%20Family%20Members.pdf?sequence=1&isAllowed=y pada pukul 01.22 WIB.
Dibuat oleh: Irma Fauzia Diedit oleh: Fauzia Ramadhani & Kresentia Aretha T.
